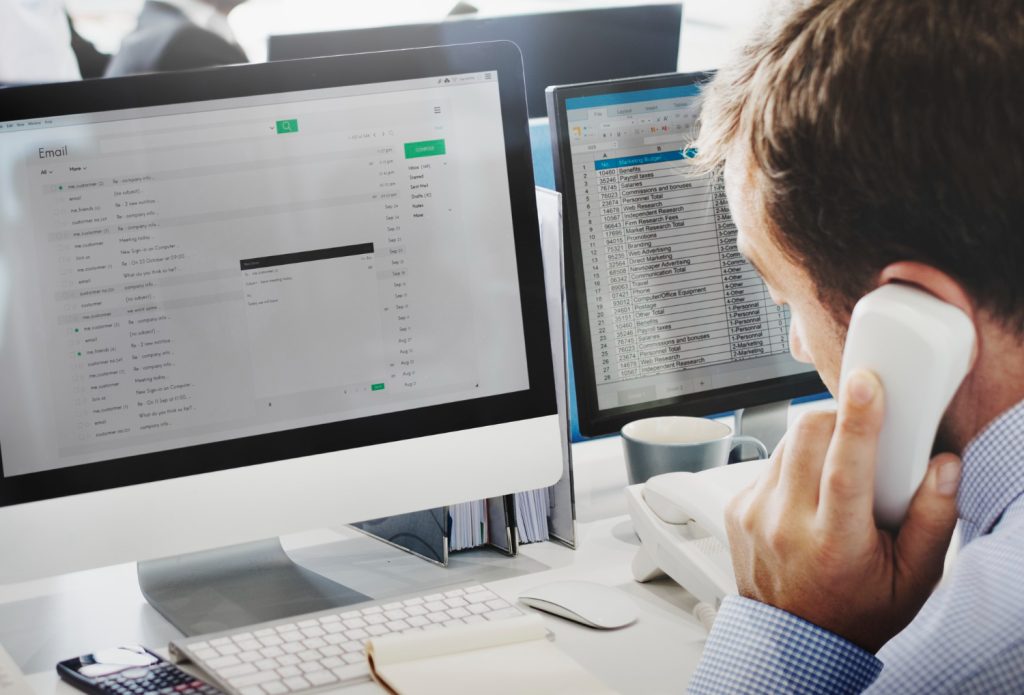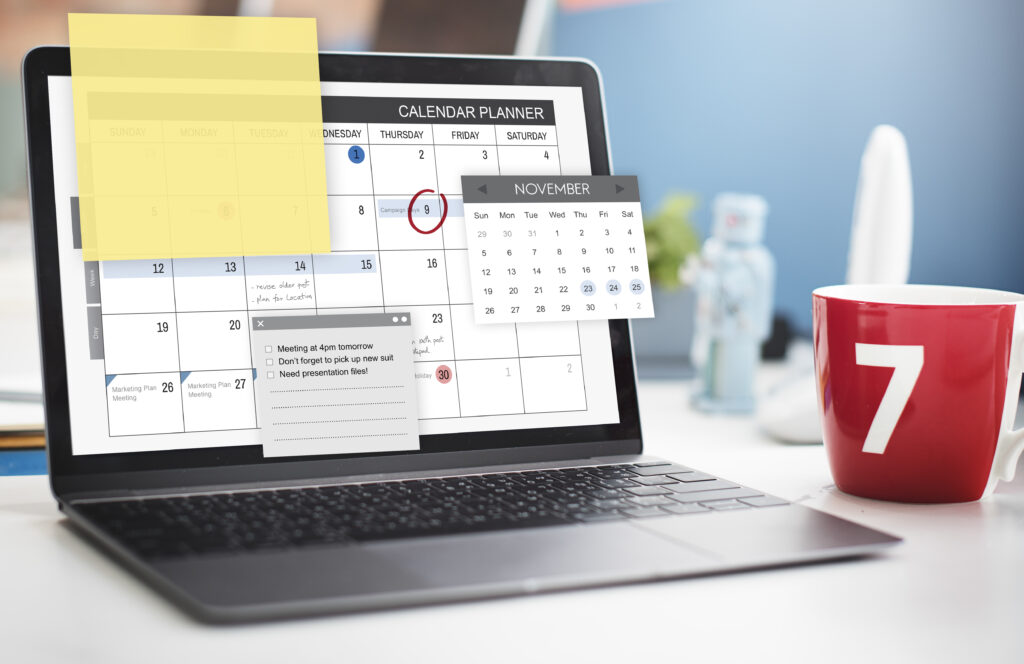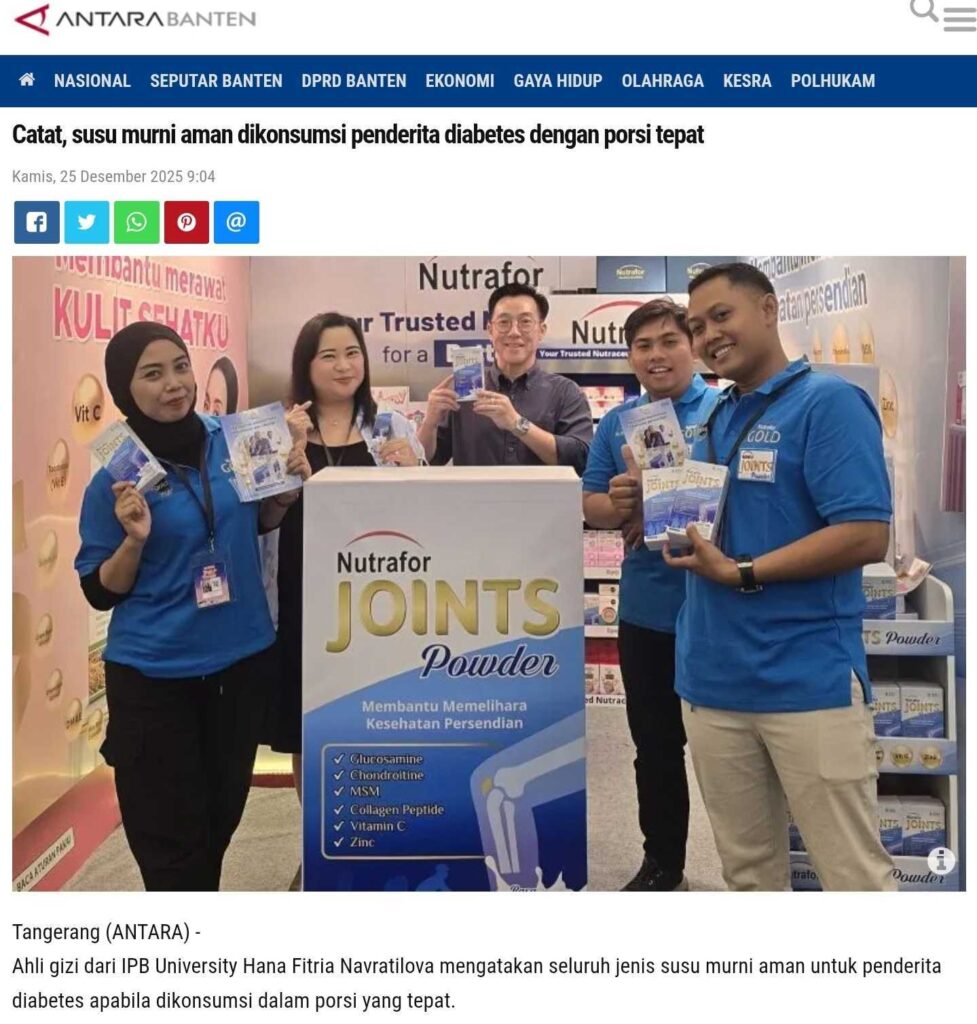Alih profesi dari dunia jurnalistik ke akademik membawa satu bekal yang sama, yaitu komunikasi adalah soal tanggung jawab. Hal itu yang dipegang teguh oleh Dede Suprayitno, dosen komunikasi di Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media UPN Veteran Jakarta.
Ia juga pernah menghabiskan hampir 7 tahun di industri media sebagai jurnalis, antara lain di Jawa Pos, Kontan.co.id, dan terakhir di ruang redaksi CNBC Indonesia sebagai produser, menyaksikan langsung bagaimana satu berita bisa mengubah persepsi publik, bahkan menggerakkan pasar.
Kini, dari balik papan tulis dan layar presentasi, sebagai dosen komunikasi, Dede berbagi pandangan dengan RadVoice Indonesia tentang bagaimana dunia media, pendidikan, dan teknologi saling berkaitan, serta kenapa literasi komunikasi hari ini jadi kebutuhan paling mendesak.

Baca juga: 3+ Kesalahan Menjalankan Profesi Humas menurut Dosen Unpad
Dari Redaksi ke Ruang Kelas: Memahami Dinamika Baru Media
Dede berpandangan bahwa praktik komunikasi media saat ini sangat dinamis. Tidak hanya di industri, tetapi juga di dunia akademik. Dia sangat merasakan maraknya penggunaan artificial intelligence (AI).
Baginya, AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan titik balik baru bagi cara kita memproduksi dan memahami informasi. Dunia kerja berubah, ruang belajar pun ikut bergeser.
“Terkadang, kampus dipandang seperti menara gading, padahal idealnya perguruan tinggi dan industri saling berkolaborasi. Akademisi perlu turun ke lapangan, sementara industri butuh refleksi dari dunia pendidikan,” terang Dede.
Dari pengalamannya di beberapa media nasional di Indonesia, Dede belajar bahwa teori tanpa praktik akan mudah kehilangan relevansi. Oleh karena itu, ia membawa semangat newsroom ke ruang kelas, mengubah kuliah menjadi tempat eksplorasi nyata tentang media dan etika.
Maka dari itu, sebagai dosen komunikasi, Dede berupaya menjembatani teori dan praktik. Dia biasanya menggunakan dua pendekatan utama: Case Based Learning (CBL) dan Project Based Learning (PjBL). CBL menekankan pada diskusi dan analisis kasus nyata, sementara PjBL mendorong mahasiswa menciptakan karya jurnalistik.
“Untuk mata kuliah dasar, saya gunakan CBL agar mahasiswa belajar berpikir kritis melalui kasus. Sedangkan untuk tingkat lanjut, PjBL lebih cocok karena mahasiswa bisa langsung praktik menciptakan karya jurnalistik,” kata Dede.
Dengan metode ini, pengalaman jurnalistiknya di hidup kembali di ruang kelas. Mahasiswa pun belajar tidak hanya tentang teori, tapi juga intuisi, etika, dan dinamika lapangan.
Dalam riset-risetnya tentang framing media, Dede menemukan hal yang menurutnya cukup mengagetkan: betapa kuatnya media membentuk persepsi publik.
“Media bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga memberi bingkai bagaimana fakta itu dipahami,” jelasnya. Oleh karena itulah, literasi media menjadi penting.
Menurut Dede, hasil penelitian seharusnya tidak berhenti di jurnal ilmiah semata. Justru, kata dia, riset perlu dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, agar manfaatnya dirasakan publik.
Dede percaya bahwa pendidikan komunikasi sejatinya adalah upaya mencerdaskan masyarakat agar tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga penafsir yang cerdas terhadap realitas media.

Baca juga: Peran Komunikasi Publik Humas LPSK Alfaddillah: Menjaga Suara yang Tak Terdengar
Menjaga Integritas di Tengah Banjir Informasi
Dede lebih lanjut mengatakan bahwa tantangan terbesar jurnalis dan dosen di era digital, adalah mengenai integritas informasi.
“Lanskap media berubah drastis, apalagi sejak AI hadir. Bagi jurnalis, ini berarti harus menyesuaikan diri dengan sistem baru. Sementara bagi dosen, berarti harus lebih hati-hati terhadap penggunaan AI dalam karya akademik,” kata Dede.
Ia menegaskan, penggunaan teknologi tanpa pedoman bisa berujung pada pelanggaran etika.
“Kementerian sudah memberi panduan, tapi kadang penggunaan AI bisa kebablasan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Ini yang perlu diwaspadai,” terangnya.
Sementara bagi komunikator publik, tantangannya adalah memahami konteks budaya audiens yang semakin beragam.
“Pesan yang sama bisa ditafsirkan berbeda tergantung latar belakang penerimanya. Itulah mengapa empati budaya sangat penting,” kata Dede.
Pentingnya Teori Komunikasi
Dede bercerita pada satu waktu mahasiswanya bertanya mengapa masih harus mempelajari teori komunikasi klasik. Lalu dia menjawab bahwa teori klasik memberi kita pijakan untuk memahami masa kini.
“Seperti halnya analisis saham, kita tidak bisa memprediksi masa depan tanpa memahami pola masa lalu,” kata Dede.
Baginya, teori komunikasi klasik membantu mahasiswa melihat evolusi pola interaksi manusia. “Dengan itu, mereka bisa memahami apa yang berubah, dan apa yang tetap.”
Jika harus memilih satu film yang merefleksikan problem komunikasi sosial hari ini, Dede menunjuk pada The Social Dilemma.
“Film itu menggambarkan sisi lain media sosial, tentang algoritma dan bagaimana persepsi publik bisa dikendalikan sistem. Itu realitas yang sedang kita hadapi,” kata Dede.
Di era post-truth, di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran dan emosi sering lebih dipercaya daripada fakta, Dede menilai literasi media dan kemampuan berpikir kritis menjadi benteng utama.
“Literasi media dibutuhkan agar kita tidak mudah terjebak dalam manipulasi informasi. Sementara berpikir kritis dan skeptis adalah fondasi agar mahasiswa bisa menilai kebenaran dengan lebih objektif,” kata Dede.
Ia menambahkan bahwa keberanian untuk berdiskusi, berdebat, dan mengkritik adalah bagian dari latihan berpikir kritis. “Komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi juga memahami konteks sosial dan dampaknya,” tegasnya.
Bersama dengan kolega sesama dosen komunikasi, Dede pernah meneliti framing pemberitaan calon presiden di beberapa media nasional seperti CNN Indonesia dan Kompas.com.
Temuannya menunjukkan bahwa objektivitas media sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan politik.
“Media sering kali kesulitan menjaga independensi karena terjepit antara idealisme jurnalistik dan tekanan pemilik modal,” ujarnya lugas.
Solusinya, menurut Dede, adalah kembali ke kode etik jurnalistik dan sepuluh elemen jurnalisme. “Nilai-nilai itu harus terus dihidupkan agar jurnalis tetap berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan.”

Baca juga: Panduan Etika dalam Doorstop untuk Jurnalis
Pengalaman paling berkesan
Ketika ditanya pengalaman paling berkesan selama menjadi jurnalis, Dede bercerita salah satunya adalah ketika riset dan susunan kalimat artikel berita dia berpengaruh pada pasar saham.
“Salah satunya saat saya menyadari bahwa berita yang kami tulis di CNBC mempengaruhi pergerakan pasar saham,” ungkapnya.
Peristiwa itu membuatnya memahami betapa besar tanggung jawab seorang komunikator. “Saya belajar bahwa pesan yang kita sampaikan bisa mengubah persepsi publik, bahkan keputusan ekonomi seseorang.”
Namun sebagai jurnalis, Dede pun tak luput dari kritik netizen. Dirinya pernah menghadapi komentar pedas di YouTube terhadap salah satu konten video tayangan CNBC Indonesia. Namun ia menganggap itu bagian dari dinamika komunikasi publik.
“Selama tidak melanggar kode etik, kritik adalah hal wajar. Justru itu membantu kita melihat perspektif baru,” kenang Dede.
Kesimpulan
Perjalanan Dede Suprayitno adalah kisah tentang evolusi: dari mengejar fakta ke menanamkan refleksi.
Dari redaksi hingga ruang kuliah UPN Veteran Jakarta, ia terus membawa semangat yang sama, bahwa komunikasi bukan sekadar menyebarkan pesan, tapi juga menjaga nurani dan nalar publik.
Baginya, komunikasi bukan hanya soal menyebarkan informasi, tapi juga membangun kesadaran dan empati di tengah hiruk-pikuk dunia digital.
Wawancara dengan Dede Suprayitno dilakukan pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Percakapan ini telah diedit agar lebih ringkas.